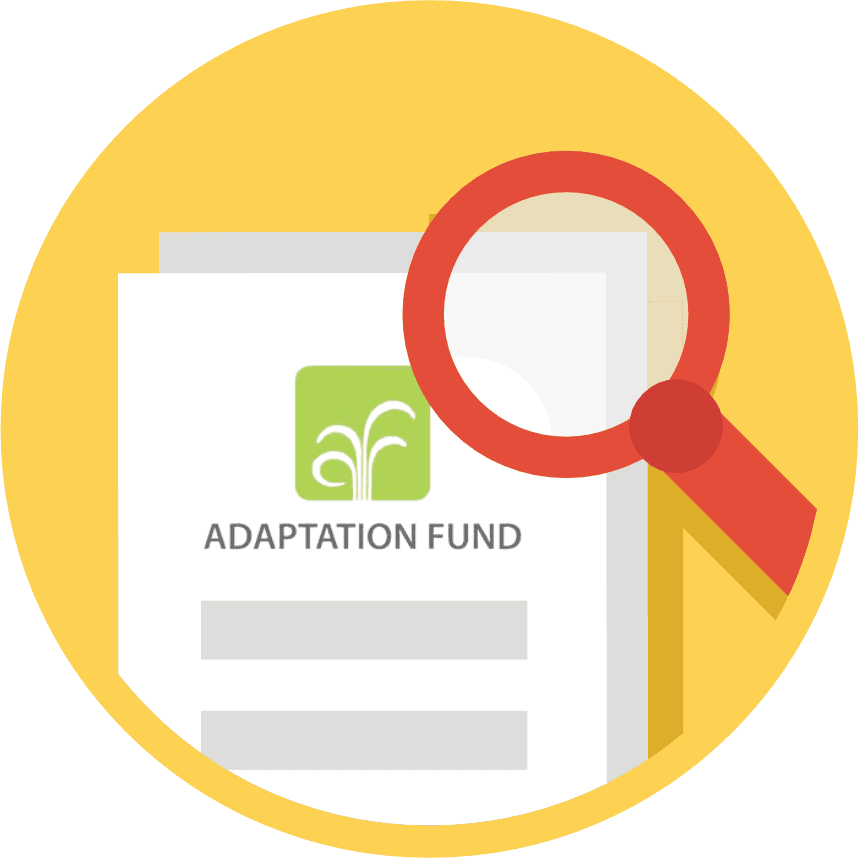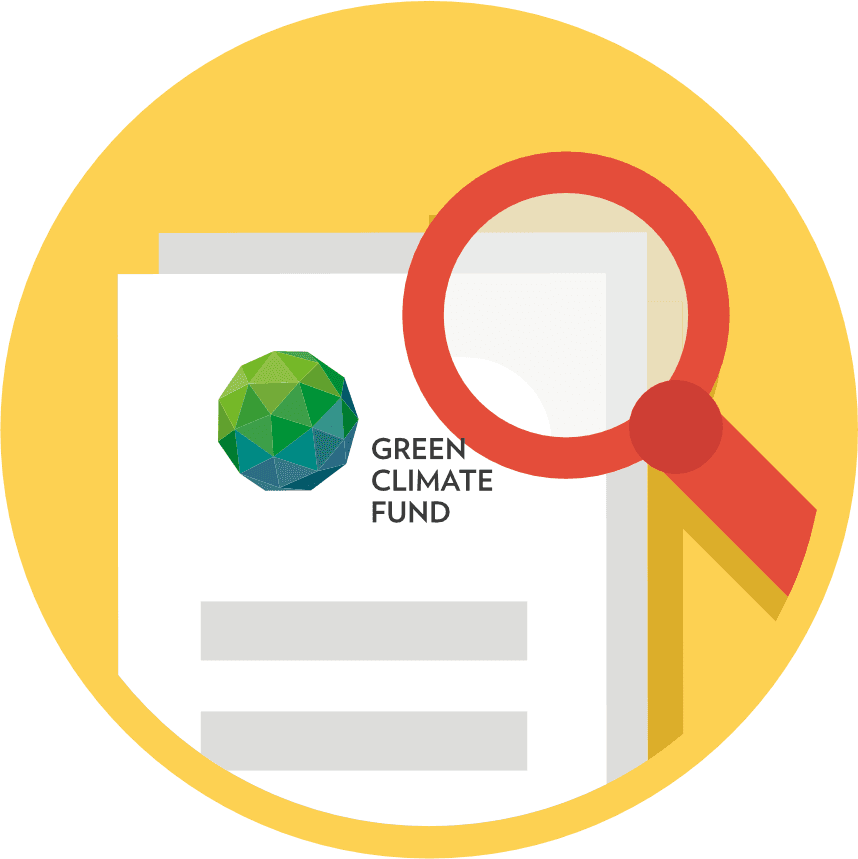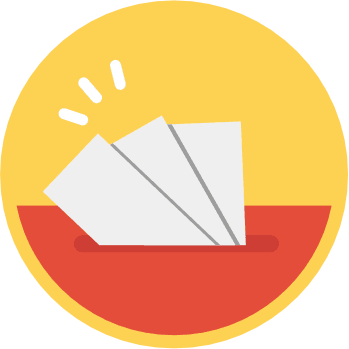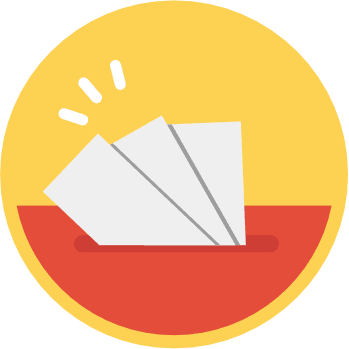Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/2021 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terbit bagi sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra.
Berdasarkan keputusan itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih pengelolaan lebih 1,1 juta hektar hutan produksi dan hutan lindung yang selama ini dikelola Perum Perhutani. Kawasan ini akan teralokasi untuk kepentingan perhutanan sosial, penataan, penggunaan, rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
Surat keputusan ini sudah beredar luas, tetapi lampiran peta KHDPK yang seharusnya jadi satu paket dengan naskah keputusan belum beredar. Masyarakat belum tahu lokasi, luas dan proporsi KHDPK.
Yang pro mendasarkan KHDPK sebagai peluang bagi partisipasi masyarakat untuk bisa mengelola hutan. Sebagian juga menganggap ini jadi jalan agar lahan hutan yang selama ini dikuasai Perhutani bisa kembali kepada rakyat dan keluar dari dalam kawasan hutan dalam bingkai reforma agraria.
Kebijakan ini juga menjadi peluang memperbaiki pengelolaan hutan yang dianggap masih feodal di bawah Perhutani, menghilangkan praktik-praktik illegal seperti pungutan liar kepada masyarakat penggarap, serta memperbaiki kondisi kawasan kritis dan terlantar.
Wacana, ide bahkan rencana restrukturisasi peran Perhutani serta reposisi dan rekonfigurasi hutan Jawa sudah digaungkan sejak lama.
Pengurangan luasan areal pengelolaan atau membagi Perhutani menjadi beberapa perusahaan atau sebagian kawasan hutan yang dikelola perusahaan negara ini diserahkan kepada pemerintah daerah sudah seringkali bahan diskusi dan kajian tetapi tidak terlaksana.
KHDPK oleh sebagain pihak dianggap sebagai ‘kemenangan’ perjuangan para petani hutan dan kelompok masyarakat sipil pendukungnya yang melawan Perhutani.

Sisi lain, para penentang kebijakan ini juga tak kalah banyak. Komisi IV DPR sedari awal menolak pengurangan luas areal Perhutani, termasuk jadi KHDPK. Alasan yang mengemuka, kekhawatiran secara ekologi dan konservasi kawasan hutan akan makin rusak dan terdegradasi. Hal ini berdasarkan implementasi pengelolaan perhutanan sosial yang justru lebih banyak merusak hutan, dibanding berhasil memperbaiki tutupan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pengelolanya.
Selain itu, meskipun secara kelembagaan Perhutani, sebagai BUMN tak dapat menolak kebijakan itu, tetapi serikat karyawan mereka menyuarakan penolakan. Mereka khawatir terkena dampak dan tidak dapat bekerja lagi karena luas areal kerja Perhutani berkurang hampir 50%. Mereka khawatir akan berdampak pada pengurangan karyawan. Penolakan juga muncul dari yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Jawa, yang mengkhawatirkan selain potensi kerusakan hutan juga konflik sosial pasca terbit KHDPK karena ada mobilisasi penggarap lahan dari luar dan menafikan para penggarap yang selama ini sudah memanfaatkan kawasan hutan.
Alih-alih sebagai upaya menyelesaikan atau meminimalisir konflik sumberdaya hutan, kalau tidak cermat dan hati-hati dalam implementasi, KHDPK justru menjadi sumber konflik atas sumberdaya hutan.
Bijak bikin kebijakan
Kalau lihat kembali, KHDPK muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang merupakan turunan dari UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. KHDPK merupakan sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa yang dikelola pemerintah untuk beberapa kepentingan itu.
Selama ini, pemerintah menugaskan Perum Perhutani mengelola hutan produksi dan hutan lindung di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2010.
Dalam PP ini disebutkan, pengurangan luas areal kerja perusahaan melalui peraturan pemerintah.
Penerbitan PP 23/2021 mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa PP, termasuk Pasal 3 (1) (2) dan (4) PP 72/2010 terkait penugasan pengelolaan hutan Jawa kepada Perhutani. Yang notabene, pasca PP ini terbit jadikan Perhutani tidak memiliki landasan hukum lagi untuk mengelola hutan Jawa.
Selanjutnya, agar tak terjadi kekosongan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 73/2021 yang kembali menugaskan kepada Perum Perhutani mengelola areal hutan produksi dan hutan lindung di Jabar, Banten, Jateng dan Jatim.
Penerbitan keputusan ini kalau dicermati merupakan diskresi menteri yang mengacu pada Pasal 293 PP 23/2021., Di sana disebutkan, ketentuan yang belum atau tak diatur dalam PP dapat diatur menteri.
Dalam bagian menimbang, SK Menlhk 73/2021 ini menyebutkan, penerbitan kebijakan merupakan upaya tak terjadi kekosongan hukum sambil menunggu peraturan pemerintah yang mengatur luasan areal hutan yang dikelola Perhutani terbit.
Para pihak kontra dengan alasan pengurangan luas areal Perhutani mesti berdasarkan PP mungkin melihat rangkaian penerbitan kebijakan ini.
Pemerintah juga sedang menyiapkan revisi PP 72/2010. Harapannya, dalam revisi PP ini tercantum luas areal kerja Perhutani. Kabar lain sedang disusun PermenLHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa. Harapannya, dalam kebijakan ini juga mengatur kelembagaan, proses transisi dan tata kelola KHDPK.
Kalau keputusan penetapan areal KHDPK terbit setelah proses revisi PP 72/2010 dan kebijakan pengaturan pengelolaan perhutanan sosial di Jawa terbit semestinya dinamika pro dan kontra atas KHDPK bisa dihindari atau setidaknya diminimalisir.
Kalau merunut kembali, kebijakan KHDPK dalam PP 23/2021 masih menjadi bagian dari turunan UU Cipta kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai UU tak konstitusional bersyarat.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah dilarang menerbitkan kebijakan strategis dan berdampak luas sampai UU Cipta Kerja yang diberikan masa revisi selama dua
tahun sejak keputusan keluar.
Apakah frase keputusan strategis dan berdampak luas dapat berlaku pada pengaturan pengelolaan hutan jawa, termasuk KHDPK? Kalau dipandang dari potensi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan serta banyaknya masyarakat maupun para pihak maka keputusan ini adalah keputusan strategi dan berdampak luas.
Sebaliknya, mungkin ada pandangan berbeda karena Mahkamah Konstitusi tak mengatur kriteria kebijakan strategis dan berdampak luas dan terlebih perhutanan sosial tak lagi menjadi program strategis nasional.
Mengatur semua, bukan sebagian
Sebaiknya, penerbitan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan hutan jawa, baik oleh Perhutani maupun para pihak lain, termasuk kelompok perhutanan sosial.
Selain menjawab berbagai kekhawatiran pihak kontra juga menjadi landasan menyusun strategi dan aksi pengelolaan KHDPK serta menghindari para free rider yang mencari keuntungan, baik ekonomi maupun politik.
Kebijakan yang baik berangkat dari proses penyusunan partisipatif dengan isi dan muatan pengaturan jelas, tidak multitafsir dan sesuai kebijakan di atasnya, hingga dipahami dan dipatuhi publik.
Dari alur kebijakan pengaturan KHDPK, meskipun menteri mempunyai kewenangan melakukan penunjukan, penetapan dan pengukuhan kawasan hutan, sebaiknya proses tidak terkesan tiba-tiba dan menjadi multitafsir apakah keputusan yang dikeluarkan sudah tepat atau tidak sesuai dengan aturan di atasnya.
Kalaupun pembuat kebijakan telah menjelaskan rinci terhadap proses dan substansi kebijakan, sementara masih ada masyarakat yang menganggap tak tepat, sebaiknya tak langsung dibawa ke ranah hukum. Tetapi bisa lakukan moderasi oleh pihak ketiga yang memahami kaidah dan proses penyusunan peraturan dan perundangan.
Sebaiknya, KLHK segera sosialisasi, dialog dan komunikasi kepada para pihak baik langsung maupun melalui jejaring media dengan menyampaikan peta areal KHDPK yang dapat menjelaskan dimana saja lokasi dan luasan KHDPK ini dan akan terlaksana untuk kepentingan apa saja.
Transparansi informasi sebagai unsur tata kelola yang baik meski dikedepankan agar tidak menjadi harapan berlebih bagi masyarakat.
Penentuan kriteria areal KHDPK sebaiknya tidak hanya oleh KLHK dan Perhutani, apalagi dengan membawa narasi bahwa yang jadi KHDPK adalah areal-areal hutan yang selama ini tak produktif, terdegrasi, rusak serta berkonflik.
Hal ini seperti menghidupkan kembali paradigma usang bahwa pemberian hak dan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat lebih menjadikan masyarakat sebagai tenaga kerja rehabilitasi dan reboisasi hutan yang sudah rusak dan dirusak pengelola sebelumnya.

Lokasi-lokasi yang selama ini dipandang berhasil dari kerjasama pengelolaan antara kelompok masyarakat dengan Perhutani semestinya justru dipilih pertama kali untuk jadi areal KHDPK agar menjadi lokasi pembelajaran dan percontohan implementasi perhutanan sosial.
Sementara itu, lokasi yang dianggap bermasalah setelah monitoring dan evaluasi sebaiknya dapat difasilitasi lebih intensif dengan melibatkan peran para pihak di daerah.
Kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang cenderung menjadi pendukung atau penentang kebijakan KHDPK, akan produktif kalau berkolaborasi bersama pemerintah daerah atau desa untuk mendampingi dan menyiapkan masyarakat di lokasi yang menjadi KHDPK agar dapat mengusulkan jadi areal pengelolaan perhutanan sosial, penataan kawasan hutan dan kepentingan lain.
Upaya ini sekaligus memastikan yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini betul-betul masyarakat setempat, yang selama ini sudah menggarap lahan. Bukan hasil mobilisasi orang-orang dari luar wilayah atau pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan pemilik modal dan politik elektoral semata.
Pengalaman selama ini pengurusan usulan perhutanan sosial atau tanah untuk obyek agraria (Tora) masih memerlukan waktu cukup lama dan fasilitasi dari para pihak. Masih sedikit sekali kelompok masyarakat yang mandiri mampu membuat dokumen usulan perhutanan sosial beserta persyaratan-persyaratannya.
Akhirnya, berharap reposisi pengelolaan hutan Jawa melalui kebijakan KHDPK membawa dampak dan manfaat tidak saja untuk masyarakat yang bergantung dari kawasan hutan, juga bisa memperbaiki kondisi dan tutupan hutan Jawa hingga dapat meningkatkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup lebih baik.
Ditulis oleh: Gladi Hardiyanto. Penulis Bekerja di Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN).
Artikel ini adalah opini penulis, dan pernah tayang di Mongabay.