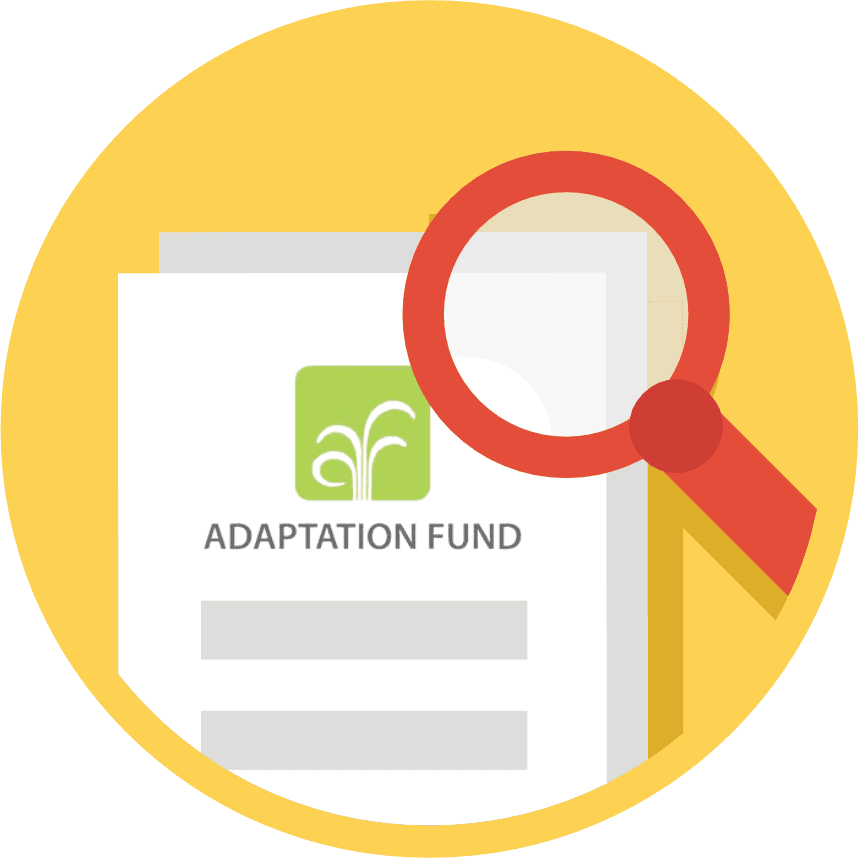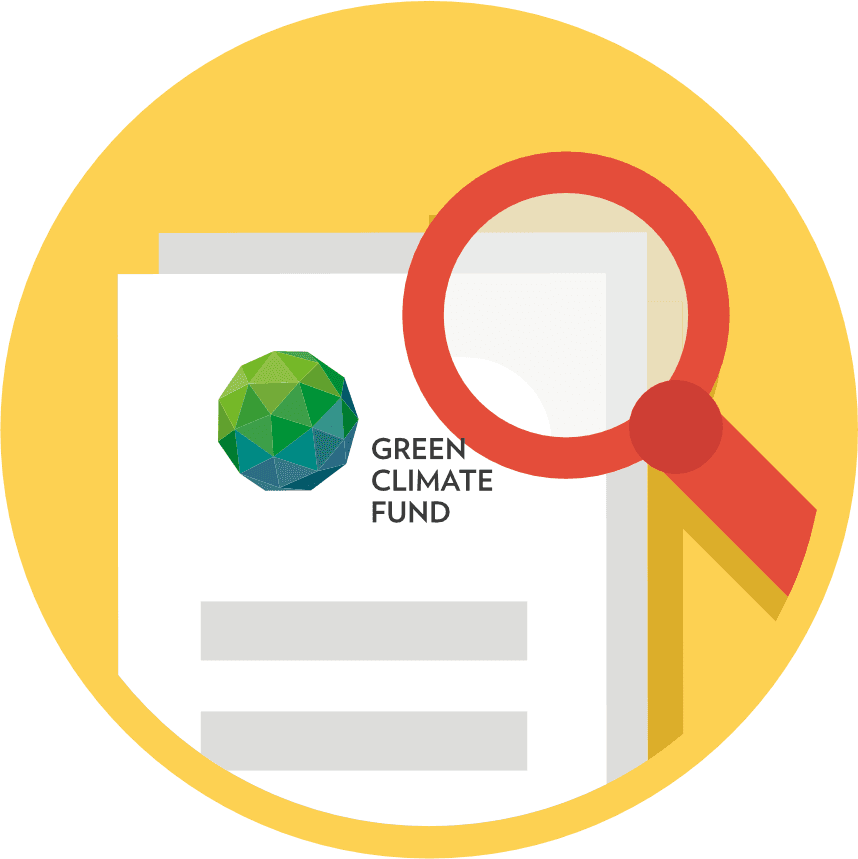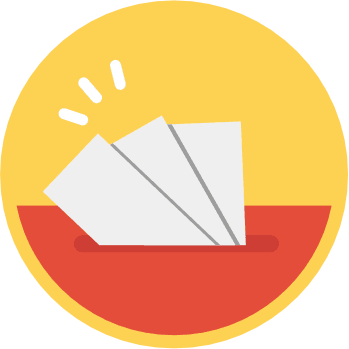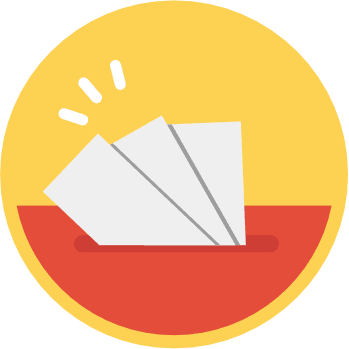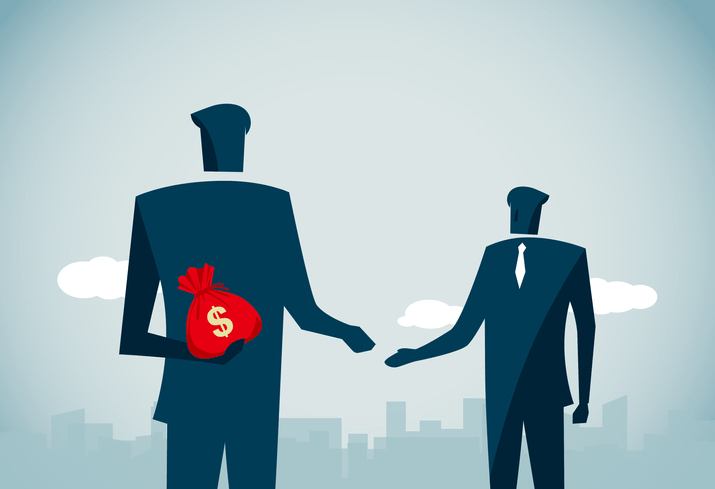
Skor Indeks Persepsi Korupsi atau corruption perception index (CPI) Indonesia jeblok 4 poin ditahun 2022 ke angka 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Situasi ini membuat peringkat Indonesia harus turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110 dari total 180 negara yang disurvei.
Skor Indonesia tak lebih baik dari rata-rata skor negara-negara Afrika Sub-Sahara (non-Afrika Utara) yang berkisar diangka 32. Lebih menyedihkan lagi, di kawasan Asia Tenggara, poisisi Indonesia berada di papan bawah. Tak usah menyebut Singapura yang menduduki peringkat negara nomor 5 terbersih dari korupsi di dunia. Skor Indonesia terpaut cukup jauh dengan Malaysia (47), Vietnam (42) dan Timor Leste (42).
Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, pemerintah akan melakukan sejumlah hal untuk merespon hasil survei lembaga Transparency International tersebut. Diantaranya adalah sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi pemerintahan.
Selintas, sejumlah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola (governance). Namun, sudahkah pemerintah dengan serius mencermati elemen apa yang membuat skor CPI indonesia longsor cukup dalam? Atau mungkin memang pemerintah tak mau ambil pusing dengan skor indeks karena sudah memiliki panacea yang mangkus untuk memberantas segala bentuk laku korupsi?
Pembajakan negara
Jika diurai masing-masing variabel penyusunnya, skor terbesar CPI Indonesia yang mengalami penurunan tajam adalah berasal dari survei risiko korupsi dalam berbisnis (International Country Risk Guide – ICRG) yang turun dari 48 di tahun 2021 menjadi 35 di tahun 2022. Survei yang dikeluarkan oleh lembaga Political Risk Service (PRS) Group yang berbasis di Amerika Serikat ini menilai resiko politik, ekonomi dan finansial suatu negara dan telah dirujuk setidaknya oleh 80% dari 500 perusahaan kelas dunia versi majalah Forbes.
Dalam hal indikator korupsi, ICRG mengukur seberapa jauh suatu negara membiarkan praktik patronase, nepotisme, kolusi, pendanaan partai secara rahasia, serta hubungan dekat yang mencurigakan antara politik dan bisnis. Dalam laporannya tentang Indonesia, PRS Group (2021) secara eksplisit mencatat peristiwa pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan serangan digital kepada aktivis anti-korupsi dan demokorasi menjadi isu sentral yang diulas.
Hal ini menandakan bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak semata-mata ditandai dengan adanya suap yang diterima pejabat publik, melainkan sudah menyasar pada kondisi yang dapat membiakkan dengan cepat prilaku-prilaku koruptif itu sendiri. Maka wajar, setiap gangguan terhadap “keseimbangan” ekosistem koruptif tersebut akan dengan cepat dimusnahkan atau setidak-tidaknya dikendalikan.
Kondisi ini yang kemudian oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko disebabkan karena melemahnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan (Kompas, 7/2). Pelemahan KPK, kooptasi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan tumpulnya pengawasan oposisi di parlemen memperkuat hipotesis itu. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menghendaki adanya pelemahan tersebut?
Sejumlah kalangan sebenarnya sudah lama menyadari bahwa jalannya roda pemerintahan nasional sudah dibajak (dan semakin menguat dalam satu dekade terakhir) oleh kepentingan bisnis atau state capture. Jika merujuk pendapat Canen dan Wantchekon (2022), state capture diartikan sebagai penyanderaan atau pembajakan negara ini terjadi lantaran adanya kepentingan pribadi (pebisnis) yang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan negara, dimana setiap tindakan pejabat-politisi dapat dilihat sebagai suatu pertukaran untuk memperkuat posisi politik kelompoknya.
Korupsi dalam konteks state capture tidak secara mudah dilihat sebagai suatu pemberian ilegal yang melawan hukum kepada pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Mengingat, dasar hukum yang dijadikan basis perbuatan pemerintah sudah lebih dulu ‘disesuaikan’ dengan keinginan pelaku usaha.
Alhasil, tindakan yang dilakukan akan tampak sah secara legal dan tidak melawan hukum. Dalam konteks ini, korupsi atau pemberian ilegal dilakukan kepada pembentuk kebijakan (decision makers) dalam rupa-rupa fasilitas atau kenikmatan. Pembiayan dana politik oleh pelaku usaha dalam ajang kontestasi elektoral yang begitu mahal merupakan bukti yang tidak terbantahkan ikhwal fenomena ‘state capture’ ini.
Realitas ini sangat gamblang terlihat dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang saat ini menjadi UU No. 4 Tahun 2020. Secara khusus, beleid ini memberikan jaminan bagi 7 (tujuh) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang habis kontraknya untuk kemudian diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dimana, dalam aturan yang berlaku sebelumnya untuk mendapatkan wilayah pertambangan harus dilakukan lelang. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena sebagian besar pemilik dari 7 perusahaan ini memiliki jalinan politik-bisnis yang kuat dengan rezim yang sedang berkuasa.
Pembenahan mendasar
Anjloknya skor CPI Indonesia yang disebabkan oleh perilaku state capture ini harus dipandang sebagai alarm bahaya baik bagi pemerintah maupun publik secara luas. Bagi pemerintah merupakan peringatan agar segera merumuskan langkah-langkah fundamental yang menyasar pada sumber korupsi, bukan pada gejalanya. Sudah saatnya meninggalkan praktik-praktik business as usual dengan memecah program-program pemberantasan korupsi ke berbagai pendekatan ke paket-paket kecil (Husodo, Kompas, 28/12/2022).
Mengingat, logika klientelisme yang menghubungkan aktor politik dan pelaku ekonomi melalui hubungan informal yang saling menguntungkan sangat sulit dipatahkan begitu sistem tersebut terbentuk dan berjalan. Proses transisi dari aturan yang klientelistik dan personalistik ke sistem yang lebih terprogram secara aturan masih jauh dari selesai bahkan di negara—negara demokrasi yang paling tekonsolidasi di dunia sekalipun (Berenschot, et.al., 2023).
Reformasi institusional yang gandrung dilakukan saat ini sejak lama disebutkan oleh Hellman dan Kaufmann (2001) tidak akan banyak berdampak untuk mempebaiki situasi state capture. Diperlukan pembenahan pada sisi ekosistem bisnis dan pemerintahan untuk kemudian secara bertahap baru menyasar reformasi kelembagaan. Membenahi situasi persaingan usaha yang monopolisitis, transparansi terhadap proses perumusan kebijakan (decision making processes) dan secara serius membenahi pendanaan partai politik adalah langkah transisi yang perlu diambil.
Sementara bagi publik secara luas, alarm bahaya harus diarahkan untuk lebih meningkatkan kesadaran (awareness) alih-alih semakin permisif pada agenda pembarantasan korupsi. Mengingat, maraknya pengungkapan kasus korupsi yang muncul di level pelaksana pemerintahan belum merepresentasikan situasi koruptif yang sebenarnya, karena sesungguhnya, prilaku korupsi di republik ini sudah bersemayam dalam arena pembentukan kebijakan negara.
Penulis: Refki Saputra, Project Officer KEMITRAAN