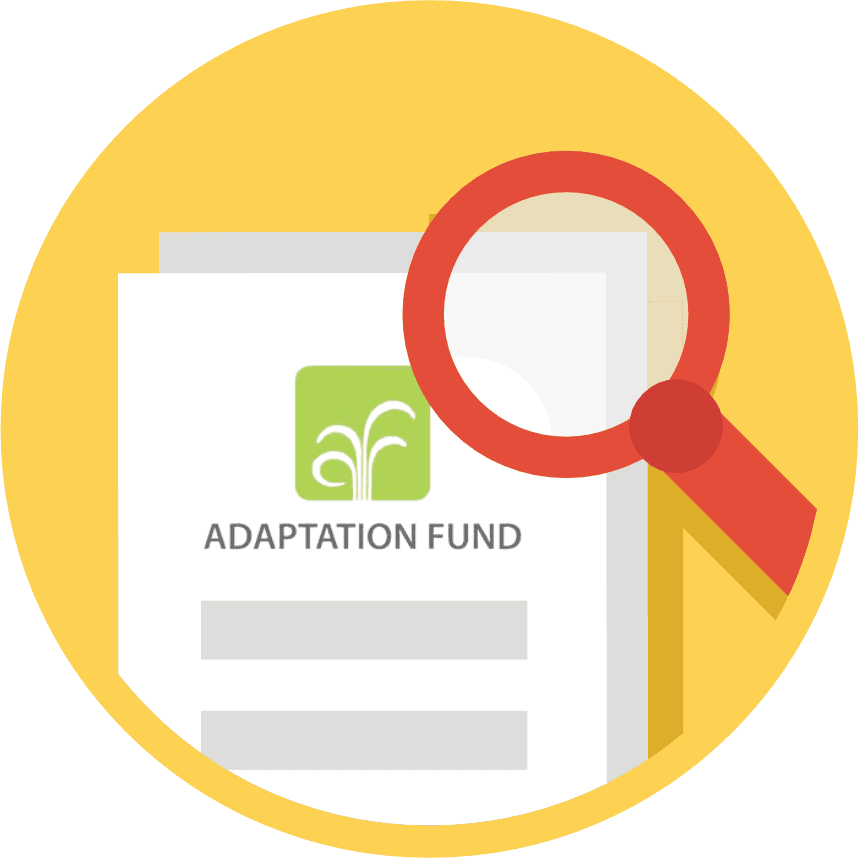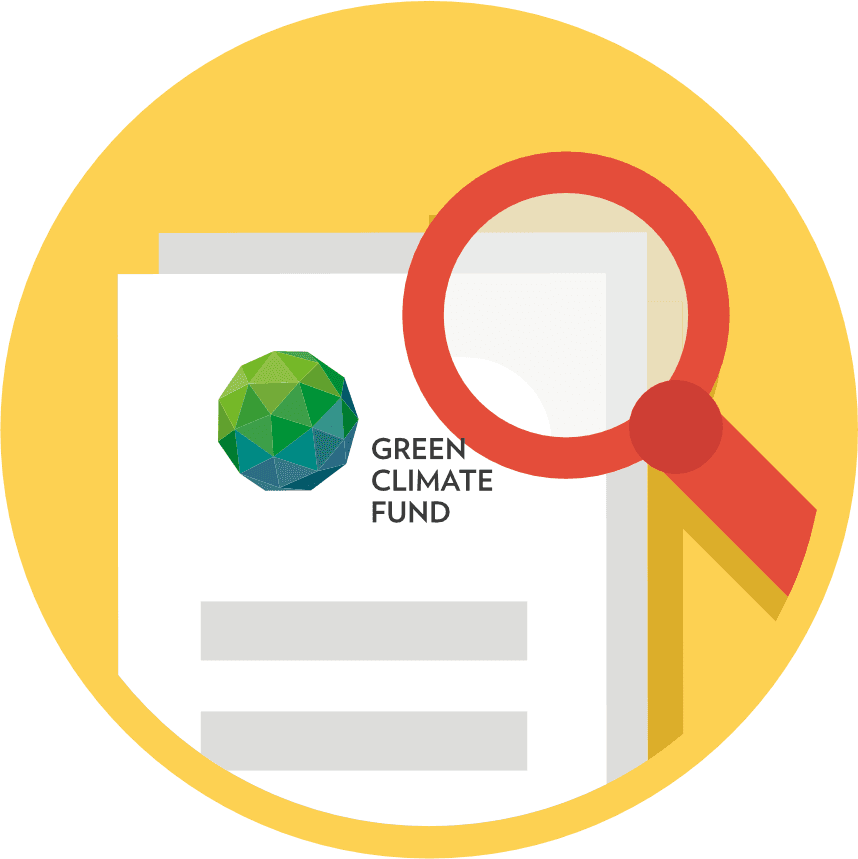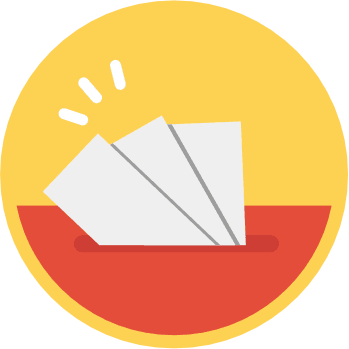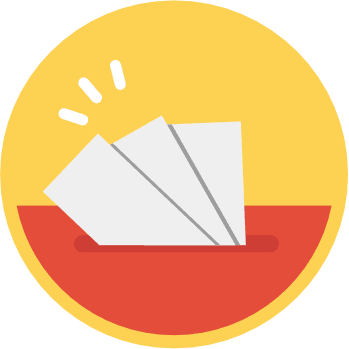Pembangunan Waduk Mbay-Lambo memicu konflik sosial yang belum selesai.
Oleh FITRIYANI ZAMZAMI
Kain tenun dari wilayah dataran tinggi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) punya warna khas: hitam dan kuning keemasan. Setiap ada hajatan, hanya tenun dengan warna tersebut yang boleh mereka kenakan.
Warna hitam yang menjadi dasar kain tenun adalah perlambang persaudaraan dan persatuan di suku-suku di sana. Sementara bebungaan dan motif lain berwarna kuning melambangkan emas. Bukan emas biasa, melainkan tinggalan para leluhur yang hanya dipakai di hajatan tertentu.
“Ini melambangkan bahwa kami berpegang pada tradisi kami, kata Mama Angela Mersiana Maw (46 tahun), salah seorang penenun anggota Suku Redu yang berdiam di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, pekan lalu.
Belakangan dua hal yang diperlambangkan corak tenunan itu terancam. Proyek besar nasional mengurai benang-benang yang selama ini menyatukan masyarakat adat di tiga kecamatan, yakni Aesesa, Aesesa Selatan, dan Nangaroro.

Daniel Dhima (59 tahun) mengenang bahwa ia sedang beraktifitas di ladangnya di Desa Ulupulu di Kecamatan Nangaroro, pada 29 April lalu. Lahan tersebut ia lanjutkan pengelolaannya dari tinggalan sang ayah.
Tanpa pertanda, 30 lebih warga, kebanyakan pemuda, datang dengan truk ke lahannya tersebut. “Mereka bawa parang, tombak, kayu, mau usir saya,” kata dia ketika ditemui rombongan jurnalis yang dibawa KEMITRAAN-Partnership for Governance Reform ke desa tersebut.
Dhima kaget bukan kepalang karena ia adalah juga kepala suku Nakabane, satu dari 17 suku yang bertempat di Ulupulu. “Mereka maki-maki leluhur. Saya tak lagi dihargai masyarakat,” ia menuturkan. Menurutnya, jika aparat kepolisian tak datang, kejadiannya bisa berdarah-darah.
Apa pasal penyerangan tersebut? Menurut Dhima, hal itu dilakukan para penyerang yang juga anggota suku Nakabane karena mereka hendak menggeser lahan adat yang ia garap. Sebagian penyerang adalah warga Ulupulu yang telah melego tanah adat garapan mereka untuk pembangunan Waduk Mbay-Lembo di wilayah tersebut.
“Mereka sudah terima ‘ganti untung’ dan tidak punya lahan lagi sehingga mau ambil saya punya lahan,” ujar Dhima.
Akibat penyerangan itu, terjadi sengketa yang diteruskan ke kepolisian. Putusan sementara, kedua pihak tak boleh beraktifitas di lahan yang mereka perebutkan. Ini fatal buat Dhima karena ia dan keluarga dekatnya tak boleh mengambil air di lokasi tersebut.”Saya ada anak balita. Di rumah saudari saya ada anak cacat. Jadi kami terpaksa beli. Syukur kalau kami ada uang, kalau kami lagi kesulitan susah juga,” ujarnya.
Cerita yang dikisahkan Dhima dan sudah diverifikasi ke pihak-pihak terkait adalah satu saja dari contoh terkoyaknya tenunan adat warga setempat seturut dibangunnya Waduk Mbay-Lambo. Pro-kontra penerimaan dan penolakan, iri dan dengki terkait uang ganti rugi, saling klaim lahan demi uang ganti rugi tersebut; semuanya membuat kerukunan yang sejak lama mengakar tercerabut.
“Sebelumnya tak ada konflik. Setelah ada terima ganti untung ini saja baru mereka mereka berani melawan,” kata Kepala Suku Nakabane. Ia tak pernah membayangkan, remaja dan pemuda anggota satu sukunya berani melawan tetua seperti sekarang. Terlebih, ia mengeklaim bahwa neneknya yang memerjuangkan bentang wilayah adat suku tersebut agar diakui negara. “Harga adat ini sudah tidak ada lagi. Bapa, kaka, tidak dihargai. Anak-anak sudah tidak hargai leluhur, leluhur dimaki-maki.”

Wacana pembangunan Waduk Mbay-Lambo ini sudah sejak 2001. Kala itu, nama resmi proyeknya adalah Waduk Mbay. Penolakan masyarakat adat yang terus menerus membuat rencana itu sempat terbengkalai.
Pada era Presiden Joko Widodo, rencana itu kembali digulirkan. Pemerintah beralasan, waduk itu nantinya untuk keperluan pengadaan air minum dan irigasi, pembangkit listrik, sampai pariwisata. Airnya diproyeksikan mengalir sampai Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo yang saat ini sebenarnya sudah memiliki Waduk Sutami.
Waduk Mbay-Lembo, yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen SDA, Kementerian PUPR; memiliki luas genangan, sabuk hijau, dan infrastruktur yang totalnya sekitar 800 hektare. Menurut pendataan Badan Pertanahan Nasional di Nagekeo, ada 555 bidang lahan adat warga terdampak di tiga desa, Yakni Ulupulu di Nangaroro, Rendubutowe di Aesesa Selatan, dan Labu Leo di Aesesa.
Tuhan memberkati bentangan luas tanah ulayat di kawasan itu dengan bukit-bukit hijau dan padang-padang yang membentang, dibelah sungai yang mengular; membentuk pemandangan dramatis. Tanahnya yang relatif subur dipakai warga yang sebagian besar petani menanam rupa-rupa tanaman seperti lontar, kemiri, pohon-pohon kayu, jambu mete, padi, jagung, dan lainnya. Ternak-ternak milik warga, sapi, kerbau, dan kambing, dilepas bebas mencari makan di padang-padang.
Sekretaris Desa Rendubutowe, Feliks Nawa menuturkan pada 2021, sosialisasi soal berlanjutnya proyek tersebut kembali digalakkan di desanya. Tiga kali kala itu, “orang-orang pemerintah” datang menyampaikan niatan mereka.
Tak ada satupun yang disambut hangat warga keseluruhan. Warga setempat meyakini, tanah adat warisan leluhur bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Mereka juga khawatir kehilangan lahan berkebun dan beternak, serta lokasi-lokasi untuk melakukan ritual adat.
Pada 2022, ajang sosialisasi itu berubah dari sekadar adu mulut jadi baku hantam, berdarah-darah. Dua orang ditangkap kepolisian saat itu. Seorang dipenjarakan selama sembilan bulan. Yang bertikai kala itu adalah kelompok pro dan kontra pembangunan waduk. “Orang pintar bujuk masyarakat hingga jadi begini,” kata dia.

Konflik pecah di Rendubutowe pada 4 April 2022. Saat itu, sekitar 20 saumlaki alias kepala suku bersama warga penerima proyek Waduk Mbay-Lambo hendak melakukan ritual adat memberkati dimulainya pengerjaan di titik nol waduk. Di sisi sebelah, para penolak yang diperkuat mama-mama Desa Rendu melakukan pencegatan.
Pemuka adat lawan pemuka adat, parang adat diacung-acungkan, mama-mama membuka baju untuk mengadang aparat polisi yang mulai main kasar. Lebih dari 23 orang ditangkap dan dibawa ke Polres Nakegeo. Sebagian mengaku jadi korban kekerasan. Surat penerimaan pembangunan waduk kemudian diteken di bawah paksaan kepolisian.
Feliks Nawa menuturkan, perselisihan antara pihak pro dan kontra tersebut membelah eratnya hubungan kesukuan di desanya. Pihak pro dan kontra waduk sama sekali tak bertegur sapa. Mereka enggan mengunjungi satu sama lain. Bahkan di gereja, selesai misa tak ada lagi obrolan-obrolan antara kedua kubu. “Jalan pulang masing-masing saja,” kata Felix.
Baru pada 2023, kemudian dilakukan rekonsiliasi adat. Apa boleh buat, waduk sudah dimulai pengerjaannya. Warga, kepala desa, dan perwakilan suku kemudian sepakat secara mandiri mencari daerah relokasi agar tak terpencar-pencar. Wilayah adat di Desa Rendubutowe mereka sepakati jadi lokasi relokasi. Sebanyak 111 kepala keluarga yang terdampak pembangunan waduk dapat kavling seluas 20 kali 40 meter. Jumlah yang sedikit saja dibandingkan lahan mereka yang ditenggelamkan.

“Waduk itu buat yang tidak mengerti tidak berguna, tapi bagi yang mengerti berguna karena untuk penyediaan air. Tapi pemerintah tidak menjelaskan,” ujar Kepala Desa Ulupulu, Yohanes B Jawa. Maksudnya, pemerintah dan perwakilannya tak pernah menjelaskan teperinci rencana buat warga setempat. “Dulu pemerintah janjikan relokasi namun sampai saat ini belum ada. Mereka seperti bilang ‘kami sudah kasih uang silakan cari sendiri’,” ia menambahkan.
Uang ganti rugi itu, menurut Yohanes tak pernah diperinci bagaimana penghitungannya. Yang dihitung selama ini hanya tanah saja. “Setelah pengadaan tanah datang tim appraisal untuk menilai tanah itu berapa harganya. Tapi, tanaman tumbuh (lahan produktif) berapa harganya, kuburan berapa harganya itu kami tidak tahu,” kata dia. Di Nagekeo, warga biasanya mengubur kerabat mereka di pekarangan rumah. Penggusuran membuat pemindahan makam ini jadi persoalan tersendiri.
“Kaka dan adik, bapa dan anak, mulai kacau balau. Karena ada pembagian uang waduk tidak adil sosialisasi tidak jelas. Sejak itu kami merasakan ada konflik besar,” kata kepala desa.
Menurutnya, dari 173 bidang yang terkena pembangunan Penataan Lokasi (Penlok) 1 Waduk Mbay-Lembo tak semua ganti ruginya terealisasi. Lahan perkebunan miliknya salah satu yang belum dibayarkan. Bidang-bidang yang belum dibayarkan ganti ruginya itu kebanyakan karena dipersengketakan. “Di Ulupulu ini ada belasan warga yang saling gugat menggugat.”

Persoalan-persoalan itu membuat dampak positif yang dijanjikan pemerintah jauh panggang dari api. “Jadi buat kami wole saja, tipu-tipu,” kata dia.
Yohanes menuturkan, uang ganti rugi yang diterima warga Ulupulu yang tanah garapan adatnya tergusur ada yang mencapai Rp 2 miliar. Namun, bahkan buat yang menerima ganti rugi bukan berarti selesai persoalan. “Namanya uang, ini ada bakso lewat selesai, tempe-tahu lewat selesai.”
Bagi warga desa yang menerima uang sebegitu besar, pendampingan manajerial adalah hal mendesak. “Yang terima uang tapi tidak bisa manajemen, uang habis. Pemerintah bilang ini uang kamu simpan baik-baik, tapi tidak ada pendampingan. Jadi yang terima uang ini sudah tidak bekerja, hanya foya-foya saja. Proses pemiskinan desa kami sudah dimulai,” kata dia menerawang kondisi mendatang bila keadaan dibiarkan seperti saat ini.
Sengketa hukum
Di Desa Rendubutowe, masyarakat Rendu membawahi tiga subsuku, yakni Suku Redu, Suku Isa, dan Suku Gaja. Tiga subsuku ini terbagi lagi menjadi sejumlah puak yang dinamai “woi” menurut bahasa setempat.
Pada Selasa (20/8/2024), Mateus Phui (62 tahun), kepala Woi Dhirikeo dari subsuku Redu baru saja pulang dari Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada dua jam perjalanan di sebelah barat Nagekeo. Ia pulang dengan tangan hampa setelah hakim di Pengadilan Negeri Ngada tak hadir untuk menyidangkan perkaranya. “Padahal biaya perjalanan Rp 200 ribu, kami sembilan orang ke sana,” tuturnya.

Ia harus ke pengadilan untuk menjalani sidang gugatan. Ia bersama perwakilan dari suku Gaja dan Isa ke pengadilan untuk menjalani sidang saling klaim antara mereka dengan suku Lado dari desa tetangga. Lagi-lagi, persoalan ganti rugi waduk jadi soalnya. “Capek. Saya ini orang desa, belum pernah ke pengadilan,” kata dia.
Ia mengatakan, saling klaim begini tak pernah ada sejarahnya di masyarakat adat Rendu. Terlebih, dahulu tanah adat memang tak boleh diperjualbelikan. Konsepnya, tanah adat milik suku tertentu bebas dipakai anggota suku tersebut untuk membangun rumah serta berkebun.
Bentangan luas wilayah berbukit-bukit di dataran tinggi Kabupaten Nagekeo itu menurutnya selama ini cukup untuk semua. Tanah lapangnya yang hijau penuh rumput bebas dipakai melepas ternak anggota suku tersebut. Jika ada anggota suku yang kembali dan meminta lahan untuk digarap, biasanya diberi. “Setelah ada waduk, setelah lihat sebagian dapat uang, baru keadaannya seperti ini,” ujarnya.
Kepala Desa Rendubutowe Yeremias Lele mengiyakan. “Dulu tidak ada sengketa lahan. ‘kalau kebun tidak saya kerjakan, kau ambil saja’,” ujarnya. Menurutnya, sebelum polemik waduk saat ini, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di Rendubutowe sangat kuat. “Sekarang seperti sudah hilang kemanusiaan.”
Bagaimanapun, pengerjaan waduk sudah telanjur berjalan. Saat Republika mengunjungi Desa Rendu, bentangan padang berbukit-bukit untuk beternak sebagian sudah digali dan diurug. Truk-truk dan kendaraan berat lalu lalang di wilayah yang nantinya akan digenangi. Ledakan-ledakan dinamit penghancur terdengar di pagi dan sore hari. Pohon-pohon tumbang, sungai tertimbun bebatuan dan tanah.
Artinya, laju pembangunan waduk tak lagi bisa ditahan. Namun, sebagian warga masih menantikan perhitungan kompensasi yang layak. Tak sedikit yang tak setuju dengan perhitungan tim appraisal dan Badan Pertanahan Nasional di Nagekeo. Mereka menilai banyak tanaman tumbuh yang tak diganti rugi, juga kuburan-kuburan di pekarangan warga. Kompensasi yang berkeadilan itu yang saat ini dinantikan warga terdampak.
Saat ini, masyarakat adat di Rendubutowe dan sekitarnya tengah didampingi program Estungkara (Kesetaraan untuk Menghapus Ketidakadilan dan Diskriminasi) yang merupakan kerjasama KEMITRAAN-Partnership for Governance Reform dan PEREMPUAN AMAN. “Kami membantu masyarakat untuk penguatan kapasitas melalui pelatihan dan melakukan pendataan menyeluruh atas aset-aset yang hilang akibat pengambilalihan lahan dalam proses ganti rugi. Data ini menjadi penting sebagai basis advokasi untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat adat,” demikian bunyi pernyataan KEMITRAAN-Partnership for Governance Reform.
Menurut mereka, penataan infrastruktur termasuk infrastruktur sosial menjadi landasan pembangunan kembali komunitas yang sudah tercerabut dari akarnya. Kedepan pendampingan akan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi lokal agar mereka tetap berdaya pascapembangunan waduk.

Kerancuan ganti rugi
Sedangkan menurut Kepala BPN Nagekeo Yohanes Fredi Malela, sedianya kerancuan soal ganti rugi lahan tersebut tak lepas dari penolakan warga. Ia menuturkan, petugas BPN sulit melakukan pengukuran karena terintimidasi oleh penolakan.
Karena pembangunan waduk harus dikebut, penghitungan yang tak sepenuhnya sempurna itu kemudian dijadikan dasar ganti rugi. Ia mengeklaim, sudah transparan menampilkan bidang-bidang dan biaya ganti ruginya di kantor desa untuk disangkal oleh warga yang keberatan.
Ada warga yang menerima hanya Rp 8 juta hingga yang terbanyak menerima Rp 3 miliar. Perhitungan itu berlandaskan nilai NJOP sekitar Rp 32 ribu per meter persegi. Saat ini, dana warga yang masih menolak atau belum setuju dengan perhitungan tim appraisal dan BPN “dititipkan” di pengadilan.
Menurutnya, masing-masing desa punya dinamikanya sendiri-sendiri terkait pembangunan waduk. Labuleo, misalnya, adalah yang paling sedikit penolakan terhadap proyek waduk. “Tapi gejolak di antara mereka besar sehingga kami terdampak,” kata Fredi Malela. Sementara penolakan paling keras terjadi di Rendubutowe.

Kepala BPN Nagekeo mengatakan, ada sekitar 100 gugatan pertanahan terkait pembangunan waduk dan tiga gugatan antarwarga. Sementara konflik horizontal juga terjadi. Ia menuturkan, dari 555 bidang yang kena dampak, sebanyak 380 sudah dibayarkan ganti ruginya. Ia memersilakan warga yang keberatan dengan ganti rugi menggugat ke pengadilan.
Kapolres Nagekeo Kombes Pol Andrey Alfian mengiyakan, pembangunan Waduk Mbay Lembo menimbulkan konflik di masyarakat. Ia berdalih, kekerasan dan tindakan represif kepolisian di masa sebelum ia menjabat tak lain karena usia muda para petugas. “Mereka ini emosinya belum stabil,” kata dia. Kedepannya, ia menjanjikan akan turun langsung menangani gejolak di masyarakat dengan menggandeng para pemangku kepentingan.
Sementara saat ditemui, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Lukas Mere mengatakan tak bisa mengerti dengan penolakan terhadap Waduk Mbay-Lambo. “Air itu kehidupan, air kok ditolak,” kata dia. “Ini negara demokrasi, kalau ada satu orang yang menolak apakah (proyek) harus dibatalkan?”.
Ia juga menilai bahwa tanah adat bukannya hal yang tak bisa ditawar. Menurutnya, leluhur suku tempatan mestinya mengerti jika sudah dibelikan tanah pengganti tanah adat.
Soal relokasi, ia mengakui pemerintah kabupaten belum memiliki rencana. Hal itu menurutnya bisa dipikirkan sembari waduk dibangun. Bagaimana dengan warga yang sudah kehilangan lahan dan rumah sementara waduk dibangun? “Bisa ditransmigrasikan,” jawab Sekda Nagekeo singkat. Atas kehilangan lahan bertani warga, ia menyarankan solusi agar warga beralih profesi menjadi nelayan saat nantinya waduk jadi.
Buat masyarakat adat di dataran tinggi Nagekeo, tak bisa sesederhana itu. Bukan perkara mudah bagi warga yang terbiasa bertani untuk tiba-tiba menjadi nelayan. Seperti hitam di kain tenun mereka, keutuhan dan persatuan suku adalah juga hal yang harus dijaga betul untuk keberlangsungan komunitas mereka.
Mereka menyadari, menghentikan pembangunan waduk adalah asa yang sudah terlampau jauh dijangkau. Ia dan rekan-rekan sukunya yang terdampak saat ini hanya bisa meminta hal lain yang mendesak: kompensasi yang adil dan pengakuan atas tanah relokasi mandiri yang mereka sepakati. “Bagaimanapun nantinya, kami harus tetap satu,” kata Mateus Phui.
Sumber: republibika.id
https://republika.id/posts/54434/waduk-datang-mengoyak-tenun-kerukunan-adat